Landasan Pembuatan RUU Perlindungan Buruh
Disampaikan dalam Pertemuan FGD Internal ABM, 28 Mei 2007
LAWAN PENJAHAN BENTUK BARU
TOLAK UUK DAN REVISINYA, BUAT UU PRO BURUH
TOLAK UUK DAN REVISINYA, BUAT UU PRO BURUH
Aliansi Buruh Menggugat (ABM) lahir sebagai jawaban atas kebutuhan persatuan kaum buruh untuk melawan Penjajahan Bentuk Baru (neo-liberalisme) yang dalam prakteknya di sektor perburuhan berupa kebijakan yang mengacu pada Labour Market Flexibelity (LMF) atau Pasar Tenaga Kerja Murah. Kebijakan ini secara kongkrit berupa sistem buruh kontrak, out sourcing, memudahkan PHK dan menghilangkan peran atau tugas Negara untuk melindungi buruh.
Untuk melegitimasi kebijakan tersebut, maka Pemerintah bersama DPR dengan didukung oleh lembaga-lembaga internasional (IMF dan ILO) membuat Paket Reformasi Hukum Perburuhan, yakni UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Ketiga paket UU ini sesungguhnya hanyalah penerus Politik Hukum Perburuhan Orde Baru.
Akan tetapi Paket Undang-Undang Perburuhan tersebut ternyata dirasa belum mencukupi untuk melancarkan kebijakan ekonomi neo-liberalisme atau kurang ramah terhadap investasi, sehingga melalui PROPENAS dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006, diperintahkan agar merevisi segala peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Undang-undang di bidang ketenagakerjaan juga direvisi agar meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
Untuk melegitimasi kebijakan tersebut, maka Pemerintah bersama DPR dengan didukung oleh lembaga-lembaga internasional (IMF dan ILO) membuat Paket Reformasi Hukum Perburuhan, yakni UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Ketiga paket UU ini sesungguhnya hanyalah penerus Politik Hukum Perburuhan Orde Baru.
Akan tetapi Paket Undang-Undang Perburuhan tersebut ternyata dirasa belum mencukupi untuk melancarkan kebijakan ekonomi neo-liberalisme atau kurang ramah terhadap investasi, sehingga melalui PROPENAS dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006, diperintahkan agar merevisi segala peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Undang-undang di bidang ketenagakerjaan juga direvisi agar meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
Dalam memenuhi kerangka inilah semua Undang-Undang yang saat ini disusun dan dibuat oleh Pemerintah bersama DPR RI.
Aliansi Buruh Menggugat menyadari bahwa keberhasilan lolosnya pembuatan Undang-Undang yang Anti Rakyat tersebut lahir dikarenakan lemahnya serikat buruh yang ada saat ini. Serikat-serikat Buruh yang besar merupakan sisa-sisa lama Orde Baru yang sejatinya mengamini kebijakan Penjajahan Gaya Baru tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan persatuan dari serikat-serikat buruh yang benar-benar berjuang untuk kepentingan kaum pekerja dan kemudian mulai berjuang di lapangan politik, yaitu lapangan pembuatan hukum.
Mengapa Aliansi Buruh Menggugat Menolak UU No. 13 dan Revisinya?
Penjajahan Bentuk Baru (neo-liberalisme) yang dalam prakteknya di sektor berupa kebijakan yang mengacu pada Labour Market Flexibelity (LMF) atau Pasar Tenaga Kerja Murah. Kebijakan ini secara kongkrit berupa sistem buruh kontrak, out sourcing, memudahkan PHK dan menghilangkan peran atau tugas Negara untuk melindungi buruh. Semua ini adalah malapetaka bagi kaum buruh. Semua malapetaka ini semuanya termaktub dalam UUK No. 13 Tahun 2003.
Selain itu juga dikarenakan UUK No. 13 Tahun 2003 hanyalah legitimasi Praktek Hukum Perburuhan Orde Baru yang selama ini dituangkan dalam segala bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan atau Keputusan Menteri yang sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang Perburuhan yang ada.
Sedangkan Revisi UUK no 13/2003 adalah usaha pemerintah dalam membangun system ketanaga-kerjaan di Indonesia yang sesuai dengan system ketenaga-kerjaan yang diinginkan oleh kaum modal saat ini yaitu sesuai dengan system neoliberalisme.
Jadi pelaksanaan revisi tersebut tidaklah terlepas dari proses penyusunan tata ekonomi dan politik Indonesia yang mengikuti tata ekonomi-politik neoliberal tersebut. Beberapa program neoliberal yang telah berhasil dilaksanakan di Indonesia hingga saat ini adalah: pencabutan subsidi pada sektor nonproduktif (BBM, pupuk, pendidikan, kesehatan, listrik dll), privatisasi perusahaan milik Negara (telkom, indosat, dll), pembebasan pasar di Indonesia untuk produk-produk import). Bagi kepentingan kaum modal, pelaksanaan system neoliberal pada hal-hal tersebut tidak lah mencukupi tanpa diikuti dengan menjalankan system neoliberal pada system ketenaga-kerjaan secara utuh, karena pada prinsipnya system neoliberal tersebut adalah systemnya kaum modal untuk mendapatkan sumber daya alam (bahan baku dan sumber energy) dan tenaga kerja dengan mudah dan murah, yang secara prinsip maupun prakteknya neoliberalisme merupakan sebuah penjajahan model barunya kaum modal!
Undang-Undang Perburuhan Model Aliansi Buruh Menggugat
Oleh karena itu ABM menjadi suatu kebutuhan untuk membuat suatu Undang-Undang Perburuhan yang benar-benar melindungi kaum buruh dan kembali pada semangat awal kemerdekaan RI.
Pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan bahwa segala bentuk penjajahan dan penindasan harus dihapuskan. Dan Pasal 27 UUD 1945 jelas-jelas menyatakan bahwa Rakyat berhak atas kerja yang layak bagi kemanusiaan.
Gagasan penghapusan segala bentuk penindasan dan eksploitasi menjadi ide dasar dari Para Pendiri Negara RI. Oleh karena itu setelah penjajah Belanda telah dihalau dengan Proklamasi Kemerdekaan, gagasan ini tetap menjadi isu besar yang hidup.
Sejak awal, Pemerintah di Indonesia dianggap bertugas untuk melindungi buruh, menjunjung tinggi hak-hak buruh dan mengusahakan kondisi kerja yang baik. Dianggap sudah pantas bahwa pemerintah berdiri di pihak buruh dalam perjuangan mereka melawan eksploitasi dan penindasan.
Oleh karena itu jelas bahwa perundang-undangan yang muncul pada awal-awal Indonesia merdeka adalah undang-undang yang melindungi buruh seperti yang terlihat dari paket perundang-undangan yang dikeluarkan, seperti: Undang-Undang Kecelakaan, UU No.33 tahun 1947; Undang-Undang Kerja, UU No. 12 tahun 1948; UU No. 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan; UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan; UU No. 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; dan UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Semua Undang-Undang tersebut dalam substansinya sangat pro-buruh.
Dalam konteks melawan Penjajahan Bentuk Baru (neo-liberalisme) inilah Undang-Undang Perburuhan yang akan dibuat oleh ABM.
Ringkasan Pokok Pikiran Dalam RUU Perlindungan Buruh
Disampaikan dalam Pertemuan FGD Internal ABM, 28 Mei 2007
Pengantar
Perjuangan kaum buruh Indonesia tengah memasuki babak baru. Setelah sekian lama, gerakan buruh Indonesia akhirnya memahami bahwa perjuangan untuk mencapai kesejahteraan harus dilancarkan di dua medan pertempuran yang berbeda namun saling menunjang dan saling melengkapi. Yang pertama adalah di bidang kepastian adanya sistem perundang-undangan yang membela buruh. Sementara yang kedua adalah membangun perangkat untuk memastikan dan mengawal pelaksanaan UU tersebut di lapangan.
Saat ini, kedua lapangan perjuangan itu masih belum dapat dimasuki oleh gerakan buruh di Indonesia. Oleh karena itulah ABM merancang proses pembuatan UU pro buruh yang seyogyanya merupakan hasil partisipasi sebanyak mungkin kaum buruh Indonesia. Diharapkan melalui program pembuatan rancangan UU yang disebut RUU Perlindungan Buruh ini, kaum buruh Indonesia sudah mulai memasuki lapangan perjuangan yang pertama.
Melalui proses pembahasan yang disertai partisipasi anggota-anggota serikat buruh yang tergabung dalam ABM ini, diharapkan akan kesepakatan politik yang telah dibuat dalam Konferensi Pendirian ABM, di bulan Juli 2006, akan semakin kokoh terikat. Dengan adanya kesamaan visi dan misi ini diharapkan kesatuan langkah organisasional akan semakin mudah tercapai. Diharapkan juga tumbuhnya kepercayaan diri pada kaum buruh Indonesia bahwa buruh juga adalah warganegara yang berhak dan wajib mengikuti proses bernegara – bukan sekedar pasrah menjadi korban perundang-undangan yang tidak berpihak pada buruh.
Saat ini, kedua lapangan perjuangan itu masih belum dapat dimasuki oleh gerakan buruh di Indonesia. Oleh karena itulah ABM merancang proses pembuatan UU pro buruh yang seyogyanya merupakan hasil partisipasi sebanyak mungkin kaum buruh Indonesia. Diharapkan melalui program pembuatan rancangan UU yang disebut RUU Perlindungan Buruh ini, kaum buruh Indonesia sudah mulai memasuki lapangan perjuangan yang pertama.
Melalui proses pembahasan yang disertai partisipasi anggota-anggota serikat buruh yang tergabung dalam ABM ini, diharapkan akan kesepakatan politik yang telah dibuat dalam Konferensi Pendirian ABM, di bulan Juli 2006, akan semakin kokoh terikat. Dengan adanya kesamaan visi dan misi ini diharapkan kesatuan langkah organisasional akan semakin mudah tercapai. Diharapkan juga tumbuhnya kepercayaan diri pada kaum buruh Indonesia bahwa buruh juga adalah warganegara yang berhak dan wajib mengikuti proses bernegara – bukan sekedar pasrah menjadi korban perundang-undangan yang tidak berpihak pada buruh.
Pokok-pokok Pikiran yang Menjiwai RUU Perlindungan Buruh
Pokok-pokok pikiran yang diuraikan di sini disusun untuk mendukung Program Perjuangan ABM, terutama penentangan terhadap Sistem Penjajahan Gaya Baru, dan turunannya berupa sistem kerja fleksibel, kerja kontrak dan outsourcing.Mengembalikan Hukum Perburuhan sebagai instrumen Perlindungan Bagi Buruh
Hukum Perburuhan dari sejarah terbentuknya merupakan hukum yang bersifat melindung kaum pekerja dari praktek dan prinsip-prinsip hukum yang akan merugikan kaum pekerja secara individual. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Buruh yang akan dirumuskan oleh ABM memiliki prinsip dasar:
• Menolak “Kesetaraan di Mata Hukum”: UU Perlindungan Buruh dirancang untuk mencegah terjadinya penindasan dan penghisapan terhadap buruh
• Menolak Seluruh Sistem Perburuhan Neoliberalisme (Penjajahan Gaya Baru)
• Menolak Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perburuhan
• Negara harus berpihak pada Buruh dalam pertikaian perburuhan dan tegas menghukum pelanggaran yang dilakukan pengusaha atas hak buruh
Mengenai Hubungan dan Perselisihan Industrial
Pada prinsipnya, RUU ini menawarkan perlindungan terhadap posisi buruh dalam tiap sengketa industrial dan pengambilan keputusan mengenai ketenagakerjaan dalam perusahaan. Oleh karena itu, RUU Perlindungan Buruh menentang sistem perundingan bipartit, karena posisi tawar buruh menjadi sangat lemah dalam perundingan. Hubungan industrial yang diidam-idamkan dalam RUU Perlindungan Buruh ini adalah jenis hubungan yang menganggap buruh sebagai satu kesatuan, sekalipun berbeda serikat, namun satu kepentingan ketika berhadapan dengan kepentingan pengusaha. Ini merupakan tangkalan terhadap sistem hubungan industrial saat ini yang menganggap buruh harus saling bersaing sesama buruh dan sesama serikat buruh, tidak memberi perlindungan pada posisi buruh yang lemah ketika berunding dengan pengusaha dan tidak menjamin keleluasaan buruh untuk berserikat di perusahaannya.
RUU Perlindungan Buruh juga mengambil sikap tegas bahwa segala macam keputusan mengenai ketenagakerjaan (termasuk soal pekerjaan, upah dan jaminan-jaminan lain) harus dibicarakan dengan serikat buruh. RUU mengambil sikap yang mengistimewakan kedudukan serikat pekerja/buruh dalam perundingan, dibanding jika seorang pekerja berusaha melakukan negosiasi tanpa melalui serikat buruh. Ini untuk mendorong pekerja berserikat, sekaligus membuat pengusaha tidak bisa mengambil keputusan sewenang-wenang tentang ketenagakerjaan tanpa persetujuan serikat pekerja/buruh.
Untuk menangkal upaya pengusaha mengakali apa yang diatur dalam RUU ini (jika kelak disahkan) maka dibuatlah beberapa perubahan dalam rincian definisi (uraian istilah). Perubahan yang mendasar antara lain dilakukan pada definisi hubungan kerja (yakni hanya mencakup unsur adanya pekerjaan dan upah), serta pekerja yang dikecualikan sebagai buruh karena posisinya dengan majikan, siapa saja yang boleh menjadi pengurus serikat buruh (untuk mencegah pengusaha menyisipkan orangnya ke dalam serikat buruh), dll.
Perlindungan lain yang diberikan secara penuh, tanpa syarat, adalah perlindungan atas hak mogok. RUU Perlindungan Buruh menganggap bahwa mogok adalah senjata utama pekerja/buruh berhadapan dengan kecurangan pengusaha, serta untuk menggalang solidaritas antar sesama buruh dan sebagai alat politik kaum buruh.
Mengenai Kesetaraan Kesempatan Kerja
Pada garis besarnya, RUU Perlindungan Buruh mengusulkan adanya peraturan yang secara keras melarang terjadinya diskriminasi berdasarkan Suku, Agama, Ras, Pandangan Politik, Jenis Kelamin dan Usia. Prinsip anti-diskriminasi ini harus diberlakukan baik dalam proses pelatihan tenaga kerja, penerimaan dan seleksi pekerja baru, proses kerja sehari-hari, penggajian dan pemberian benefit maupun dalam persoalan perselisihan industrial. Dengan demikian diharapkan tiap individu pekerja benar-benar dihargai menurut keahliannya, bukan berdasarkan penilaian-penilaian lain yang sifatnya suka atau tidak suka.
Mengenai Jaminan Kepastian dan Keamanan Kerja
RUU Perlindungan Buruh mengambil posisi yang sama sekali bertentangan dengan posisi yang diambil oleh UUK no 13/2003. RUU Perlindungan Buruh berpijak pada anggapan bahwa buruh bukan sekedar “faktor produksi” melainkan manusia, sekaligus warganegara yang harus dilindungi ketika berhadapan dengan anasir-anasir yang berkehendak memiskinkannya – terlebih lagi jika anasir itu adalah anasir-anasir asing yang masuk ke Indonesia dengan niat menjalankan penjajahan gaya baru. Dengan demikian, dalam soal inilah RUU Perlindungan Buruh mengambil sikap paling keras: membatasi dengan ketat diberlakukannya sistem kontrak dan melarang diterapkannya outsourcing.
Dalam teknis pelaksanaannya, sikap yang diambil oleh RUU ini niscaya menghadapi banyak jebakan-jebakan sistem industrial dan hukum yang telah berlaku. Oleh karenanya, RUU Perlindungan Buruh mengambil langkah lebih mendasar yakni mengubah batasan tentang “pekerja” atau “buruh”. Dengan mengambil langkah ini, RUU Perlindungan Buruh tidak hanya melindungi mereka yang selama ini dianggap sebagai pekerja “formal” melainkan semua orang yang harus bekerja pada orang jika ingin mendapat penghidupan.
Mengenai Upah dan Pesangon
Pandangan RUU Perlindungan Buruh masih belum keluar dari lingkup teori kapitalisme mengenai upah minimum, yakni jumlah yang dibutuhkan agar buruh dapat melanjutkan kehidupannya dan datang lagi bekerja keesokan harinya. Hanya saja, RUU Perlindungan Buruh menganggap kaum pekerja sebagai warganegara yang berhak mendapatkan kesejahteraan, sehingga “hidup” dan “kehidupan” yang dimaksudkan dalam RUU ini adalah hidup layak. Oleh karena pertimbangan ini pula maka dalam RUU ini tidak dipakai istilah Upah Minimum, melainkan Upah Layak.
RUU ini juga dibuat berdasarkan sikap politik bahwa semua buruh Indonesia adalah sebangsa setanah air. Oleh karena itu, kesejahteraan yang didapatkan pun harus merata. Bukan lagi “makan tidak makan yang penting kumpul” melainkan “kumpul-kumpul karena mau makan enak.” Maka, betapapun sulit penyelenggaraan teknisnya, RUU ini mengambil sikap untuk memperjuangkan Upah Layak Nasional, yang berlaku di manapun di seluruh tanah air.
Di samping itu, karena persoalan upah merupakan salah satu hal yang paling sering diakali oleh pengusaha, maka RUU ini memuat dengan rinci komponen apa saja yang harus dihitung sebagai upah pokok. Kebanyakan tunjangan yang selama ini hanya dapat diperoleh melalui perjuangan mati-matian dicantumkan sebagai komponen upah pokok – yang kelak akan berpengaruh pada penentuan jumlah pesangon yang semakin besar. Ketentuan yang keras soal pesangon ini penting karena ini juga salah satu unsur yang vital dalam perjuangan menentang PHK massal dan pengubahan kerja tetap menjadi kerja kontrak/outsourcing.
Mengenai Dewan Perlindungan Buruh
RUU Perlindungan Buruh menganggap bahwa dalam masa peralihan, di mana serikat-serikat buruh tengah memperkuat dirinya agar setara posisi tawarnya dalam perundingan dengan pengusaha, diperlukan perlindungan Negara secara resmi atas posisi serikat buruh. Oleh karena itu RUU ini juga mencakup aturan-aturan pembentukan Dewan Perlindungan Buruh, yang akan diisi oleh wakil-wakil serikat-serikat buruh di tiap tingkatan administrasi negara.
Mengenai hubungan RUU Perlindungan Buruh dengan UU lain
Disadari bahwa UUK no 13/2003 tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu bagian dari paket UU pro Neoliberalisme, yang diatur melalui UU Propenas no 25/2000. Oleh karena itulah RUU ini juga mencantumkan perlunya perubahan-perubahan dalam berbagai UU lain yang mengatur tentang pelaksanaan sistem neoliberal di Indonesia.
Perlindungan Khusus Terhadap Reproduksi Manusia dan Sektor Pekerjaan Tertentu
Reproduksi manusia merupakan suatu hal yang harus dilindungi secara khusus, baik bagi perempuan yang melakukan reproduksi, maupun bagi anggota keluarga atau orang lain yang terlibat dalam proses reproduksi tersebut. Perlindungan ini meliputi: menstruasi, masa kehamilan, masa kelahiran dan setelah melahirkan untuk memelihara anak.
Beberapa sektor pekerjaan yang selama ini tidak terlindungi dan mengalami penghisapan yang berlebihan harus diatur secara khusus, yaitu: Buruh Migran, Transportasi, Perkebunan/Agraria/Nelayan, Pertambangan dan Migas, serta sektor Domestik atau Buruh yang bekerja di sektor usaha kecil.
RUU Perlindungan Buruh juga mengambil sikap tegas bahwa segala macam keputusan mengenai ketenagakerjaan (termasuk soal pekerjaan, upah dan jaminan-jaminan lain) harus dibicarakan dengan serikat buruh. RUU mengambil sikap yang mengistimewakan kedudukan serikat pekerja/buruh dalam perundingan, dibanding jika seorang pekerja berusaha melakukan negosiasi tanpa melalui serikat buruh. Ini untuk mendorong pekerja berserikat, sekaligus membuat pengusaha tidak bisa mengambil keputusan sewenang-wenang tentang ketenagakerjaan tanpa persetujuan serikat pekerja/buruh.
Untuk menangkal upaya pengusaha mengakali apa yang diatur dalam RUU ini (jika kelak disahkan) maka dibuatlah beberapa perubahan dalam rincian definisi (uraian istilah). Perubahan yang mendasar antara lain dilakukan pada definisi hubungan kerja (yakni hanya mencakup unsur adanya pekerjaan dan upah), serta pekerja yang dikecualikan sebagai buruh karena posisinya dengan majikan, siapa saja yang boleh menjadi pengurus serikat buruh (untuk mencegah pengusaha menyisipkan orangnya ke dalam serikat buruh), dll.
Perlindungan lain yang diberikan secara penuh, tanpa syarat, adalah perlindungan atas hak mogok. RUU Perlindungan Buruh menganggap bahwa mogok adalah senjata utama pekerja/buruh berhadapan dengan kecurangan pengusaha, serta untuk menggalang solidaritas antar sesama buruh dan sebagai alat politik kaum buruh.
Mengenai Kesetaraan Kesempatan Kerja
Pada garis besarnya, RUU Perlindungan Buruh mengusulkan adanya peraturan yang secara keras melarang terjadinya diskriminasi berdasarkan Suku, Agama, Ras, Pandangan Politik, Jenis Kelamin dan Usia. Prinsip anti-diskriminasi ini harus diberlakukan baik dalam proses pelatihan tenaga kerja, penerimaan dan seleksi pekerja baru, proses kerja sehari-hari, penggajian dan pemberian benefit maupun dalam persoalan perselisihan industrial. Dengan demikian diharapkan tiap individu pekerja benar-benar dihargai menurut keahliannya, bukan berdasarkan penilaian-penilaian lain yang sifatnya suka atau tidak suka.
Mengenai Jaminan Kepastian dan Keamanan Kerja
RUU Perlindungan Buruh mengambil posisi yang sama sekali bertentangan dengan posisi yang diambil oleh UUK no 13/2003. RUU Perlindungan Buruh berpijak pada anggapan bahwa buruh bukan sekedar “faktor produksi” melainkan manusia, sekaligus warganegara yang harus dilindungi ketika berhadapan dengan anasir-anasir yang berkehendak memiskinkannya – terlebih lagi jika anasir itu adalah anasir-anasir asing yang masuk ke Indonesia dengan niat menjalankan penjajahan gaya baru. Dengan demikian, dalam soal inilah RUU Perlindungan Buruh mengambil sikap paling keras: membatasi dengan ketat diberlakukannya sistem kontrak dan melarang diterapkannya outsourcing.
Dalam teknis pelaksanaannya, sikap yang diambil oleh RUU ini niscaya menghadapi banyak jebakan-jebakan sistem industrial dan hukum yang telah berlaku. Oleh karenanya, RUU Perlindungan Buruh mengambil langkah lebih mendasar yakni mengubah batasan tentang “pekerja” atau “buruh”. Dengan mengambil langkah ini, RUU Perlindungan Buruh tidak hanya melindungi mereka yang selama ini dianggap sebagai pekerja “formal” melainkan semua orang yang harus bekerja pada orang jika ingin mendapat penghidupan.
Mengenai Upah dan Pesangon
Pandangan RUU Perlindungan Buruh masih belum keluar dari lingkup teori kapitalisme mengenai upah minimum, yakni jumlah yang dibutuhkan agar buruh dapat melanjutkan kehidupannya dan datang lagi bekerja keesokan harinya. Hanya saja, RUU Perlindungan Buruh menganggap kaum pekerja sebagai warganegara yang berhak mendapatkan kesejahteraan, sehingga “hidup” dan “kehidupan” yang dimaksudkan dalam RUU ini adalah hidup layak. Oleh karena pertimbangan ini pula maka dalam RUU ini tidak dipakai istilah Upah Minimum, melainkan Upah Layak.
RUU ini juga dibuat berdasarkan sikap politik bahwa semua buruh Indonesia adalah sebangsa setanah air. Oleh karena itu, kesejahteraan yang didapatkan pun harus merata. Bukan lagi “makan tidak makan yang penting kumpul” melainkan “kumpul-kumpul karena mau makan enak.” Maka, betapapun sulit penyelenggaraan teknisnya, RUU ini mengambil sikap untuk memperjuangkan Upah Layak Nasional, yang berlaku di manapun di seluruh tanah air.
Di samping itu, karena persoalan upah merupakan salah satu hal yang paling sering diakali oleh pengusaha, maka RUU ini memuat dengan rinci komponen apa saja yang harus dihitung sebagai upah pokok. Kebanyakan tunjangan yang selama ini hanya dapat diperoleh melalui perjuangan mati-matian dicantumkan sebagai komponen upah pokok – yang kelak akan berpengaruh pada penentuan jumlah pesangon yang semakin besar. Ketentuan yang keras soal pesangon ini penting karena ini juga salah satu unsur yang vital dalam perjuangan menentang PHK massal dan pengubahan kerja tetap menjadi kerja kontrak/outsourcing.
Mengenai Dewan Perlindungan Buruh
RUU Perlindungan Buruh menganggap bahwa dalam masa peralihan, di mana serikat-serikat buruh tengah memperkuat dirinya agar setara posisi tawarnya dalam perundingan dengan pengusaha, diperlukan perlindungan Negara secara resmi atas posisi serikat buruh. Oleh karena itu RUU ini juga mencakup aturan-aturan pembentukan Dewan Perlindungan Buruh, yang akan diisi oleh wakil-wakil serikat-serikat buruh di tiap tingkatan administrasi negara.
Mengenai hubungan RUU Perlindungan Buruh dengan UU lain
Disadari bahwa UUK no 13/2003 tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu bagian dari paket UU pro Neoliberalisme, yang diatur melalui UU Propenas no 25/2000. Oleh karena itulah RUU ini juga mencantumkan perlunya perubahan-perubahan dalam berbagai UU lain yang mengatur tentang pelaksanaan sistem neoliberal di Indonesia.
Perlindungan Khusus Terhadap Reproduksi Manusia dan Sektor Pekerjaan Tertentu
Reproduksi manusia merupakan suatu hal yang harus dilindungi secara khusus, baik bagi perempuan yang melakukan reproduksi, maupun bagi anggota keluarga atau orang lain yang terlibat dalam proses reproduksi tersebut. Perlindungan ini meliputi: menstruasi, masa kehamilan, masa kelahiran dan setelah melahirkan untuk memelihara anak.
Beberapa sektor pekerjaan yang selama ini tidak terlindungi dan mengalami penghisapan yang berlebihan harus diatur secara khusus, yaitu: Buruh Migran, Transportasi, Perkebunan/Agraria/Nelayan, Pertambangan dan Migas, serta sektor Domestik atau Buruh yang bekerja di sektor usaha kecil.
Penutup.
Apa yang dilakukan ABM hari ini adalah satu langkah awal untuk memasuki panggung perjuangan yang sama sekali baru. Biasanya, orang menganggap sinis upaya-upaya terobosan semacam ini. Namun, pada saat ini, baru ABM yang membuktikan dirinya sanggup melangkah memanggul beban sebagai perintis jalan ke arah perjuangan buruh yang lebih tinggi dan lebih berat – namun sekaligus mendekatkan kaum buruh pada kesejahteraan.






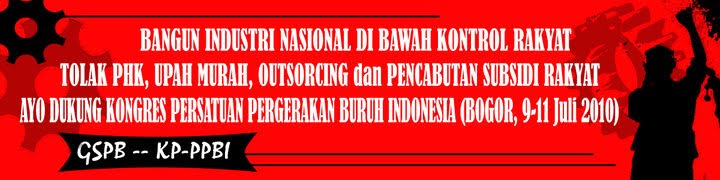
|