Pendahuluan:
Mengenali akar persoalan pada kaum buruh
(untuk komponen upah layak versi ABM, bisa di klik di sini)
Perjuangan tentang upah adalah perjuangan yang telah ada sejak adanya sistem ekonomi yang memisahkan kepemilikan antar kaum pemilik modal dengan kaum pekerja/buruh. Perjuangan tentang upah tahun lalu masih cukup jelas dalam ingatan kita bahwa hampir setiap kota/kabupaten hingga propinsi ratusan hingga ribuan buruh berjuang dengan cukup berani untuk memastikan nilai upah yang didapat untuk tahun depan lebih baik dari upah saat ini. Persatuan dan perjuang yang terjadi ditiap kota nyaris menjadi sebuah pertarungan yang terpisah-pisah, tidak pernah kita mendengarkan adanya seruan untuk juga memperjuangkan nilai upah yang lebih baik untuk kota lain, hal ini juga diperburuk dengan belum utuhnya pemahaman perjuangan kita tentang upah dan kaitan perjuangan upah dengan perjuangan sejati kita kaum buruh. Kenaikan upah (terkadang berapapun jumlahnya) sering sudah mampu meredakan perjuangan yang sebelumnya cukup menggelora, refleksi terhadap perjuangan buruh tentang upah tahun lalu adalah bahwa mayoritas dari kaum buruh belum mengetahui secara benar apa yang menjadi akar persoalan penyebab upah yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah jauh dari harapan kita sebagai manusia.
Refleksi perjuangan kaum buruh selama ini adalah bahwa persoalan-persoalan yang timbul dalam persoalan perburuhan dan persoalan rakyat lainnya selama ini adalah akibat kebijakan politik pemerintahan nasional kita yang sangat tidak berpihak pada keinginan rakyat mayoritas dinegeri ini. Pemerintahan nasional hingga saat ini adalah pemerintahan yang sangat tergantung kepada kepentingan kaum modal internasional mereka menyediakan dirinya menjadi agen untuk memuluskan kepentingan kaum modal di Indonesia. Dalam menjalankan skenario ekonominya kaum modal internasional terorgasiskan dengan cukup rapi baik secara ide maupun organisasi kerjanya. Secara ide, yang menjadi landasan bergerak kaum modal saat ini adalah sistem terkini dari kapitalisme yaitu sistem ekonomi neoliberlisme, dan secara organisasi kaum modal ini menggunakan IMF, Bank Dunia, WTO dan lembaga-lembaga multilateral lainnya untuk memastikan TNC dan MNC kaum modal tersebut dapat beroperasi dengan aman dan nyaman dinegara yang diinginkan oleh mereka.
Tentang Neoliberalisme:
Bicara tentang neoliberalisme dikalangan serikat buruh bukanlah hal yang baru dan asing, istilah neoliberalisme sudah lama kita dengar dan kita diskusikan, tapi satu hal yang harus kita selalu ingat adalah bahwa neoliberalisme tersebut bukanlah sebuah product yang benar-benar baru, tetapi dia adalah sebuah proses revisi terhadap sistem ekonomi sebelumnya tanpa menghilangkan kerja dasar dari sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi liberal, bahkan sistem ekonomi keynesian. Sistem ekonomi liberal nya adam smith, lalu sistem “penyelamat kapitalisme awal” keynesian serta yang teranyar yaitu sistem ekonomi neoliberal adalah sama-sama sebuah sistem yang menempatkan sistem produksi yang menempatkan adanya kaum yang mempunyai modal dan kaum yang hanya bekerja didalam proses produksi.
Sistem ekonomi neoliberalisme mulai berkembang sejak tahun 1970an merupakan sebuah koreksi terhadap sistem keynesian yang telah berlaku sejak 1930an, system keynesian dikritik oleh kaum penganut neoliberal karena terlalu banyaknya campur tangan negara dalam proses pasar yang mengakibatkan pasar terdistorsi yang artinya adanya pihak ketiga yang mencampuri proses transaksi, kebebsan individu adalah hal yang paling utama. Sistem ini disebut Neo-liberal karena menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan diatur berdasarkan pandangan individu, serta pengetahuan para individu akan dapat memecahkan segala persoalan yang timbul dalam persoalan ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial bagi kaum neoliberalis, pengetahuan para individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu disalurkan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang sekali lagi berarti segala sesuatunya tergantung pada individu bukan pada organisasi, yang berarti juga paham neoliberal ini tidak percaya organisasi sebagai alat pemecahan persoalan individu.
Proses mendunianya paham ini dimulai dengan cepat setelah pada tahun 80an dua pemimpin negara maju menjadi pengikut paham ini yaitu Margaret Thatcher di Inggris dengan Thatcherism dan Ronald Reagan di Amerika Serikat dengan Reaganomicsnya. Lewat tangan kedua presiden inilah kebebasan individu dan kompetisi yang bebas diimplementasikan dan disebarluaskan dalam sebuah sistem ekonomi. Persoalan kemiskinan individu tidak lagi menjadi persoalan bagi negara karena hal tersebut menjadi sebuah yang lumrah dalam sebuah kompetisi yaitu pasti ada yang tidak mampu bertarung dalam kompetisi tersebut dan yang tidak mampu itu lah yang menjadi miskin. Implementasi awal neoliberalisme dalam sistem ekonomi membuahkan hasil meningkatnyanya angka kemiskinan baik di Inggris maupun Amerika tapi sistem ini mampu meningkatkan pendapatan yang sangat signifikan bagi para pemegang modal, misalnya di Amerika selama dekade 1980an, 10% teratas meningkat pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkat pendapatannya sebesar 50%. Hal ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah kehilangan pendapatan15%.
Yang menjadi prinsip untuk mewujudkan sistem ekonomi neoliberal ini, yaitu mengoreksi sistem ekonomi sebelumnya adalah:
1. Aturan Pasar.
Menghapus segala peraturan pemerintah yang membatasi perusahaan-perusahaan dalam berinvestasi maupun berusaha. Dan juga adanya keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Tidak ada lagi kontrol harga, sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang, jasa dan konsumen.
2. Memotong pengeluaran negara pada sektor yang tidak produktif/pelayanan sosial
Anggaran pada sektor pelayanan sosial dianggap dapat mengakibatkan pasar terdistorsi sehingga memang harus dikurangi atau bahkan dihilangkan, seperti subsidi untuk BBM, pendidikan, kesehatan anggaran untuk pengangguran dll.
3. Deregulasi.
Mengurangi atau bahkan menghilangkan paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa memberatkan pengusaha, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi;
4. Privatisasi
Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Alasan privatisasi ini adalah agar menghindarkan distorsi pasar oleh BUMN-BUMN tersebut, dan BUMN dianggap bisa menghalangi perkembangan modal privat.
Peran terpenting dalam mengglobalkan sistem neoliberal ini adalah melalui lembaga IMF, Bank Dunia dan WTO, serta pintu masuk kenegara-negara tersebut khususnya kenegara dunia ketiga adalah melalui jebakan utang, yaitu utang yang diberikan secara terus menerus tanpa ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana utang tersebut yang mengakibatkan pemerintahan nasional negara dunia tersbut menjadi kecanduan dan akhirnya tidak berdaya lagi menolak perubahan sistem ekonomi nasionalnya denga mekanisme SAP (structural Adjustment Program). Dengan SAP inilah pemilik modal besar di Internsaional mampu merubah sistem ekonomi yang sudah ada menjadi sistem ekonomi yang sesuai dengan keinginan mereka dalam mengembangakan investasi dan keuntungan. SAP ini dilakukan melalui langkah: (a) pembukaan keran impor sebebas-bebasnya dan adanya aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga kebutuhan publik.
Dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak dan ditambah lagi dengan jumlah penduduknya yang cukup besar maka Indonesia adalah negara yang memang menjadi incaran dari para kaum modal. Penggulingan Soekarno dan naiknya Soeharto adalah bagian penting dari proses penguasaan Indonesia oleh kaum modal, karena penggulingan Soekarno juga berarti menyingkirkan seting orang dan organisasi yang menolak sistem ekonomi yang memberikan kesempatan kaum modal untuk mengekspoitasi alam dan manusia sebebas-bebasnya.
Krisis ekonomi di ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya pada tahun 1997 adalah anugerah pada kaum modal internasional karena membuka kesempatan seluas-luasnya pada IMF dan Bank Dunia untuk menata ekonomi di ASEAN dan Indonesia kedalam tata ekonomi dengan sistem neoliberal melalui program SAP seperti yang mereka lakukan di amerika latin pada era-80an. Dengan ditanda-tanganinya LOI oleh Soeharto dengan presiden Bank Dunia maka mulai babak baru penguasaan ekonomi Indonesia sepennuh-penuhnya oleh kaum modal Internasional, dan hal itu dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini.
Praktek Neoliberalisme diperburuhan
Neoliberalisme yang sesungguhnya adalah kebutuhan/kepentingan dari kaum modal besar di internasional untuk dapat mengembangkan modalnya keseluruhan belahan dunia tanpa harus mengalami hambatan birokrasi pemerintahan nasional yang ada, yang artinya adalah bahwa kaum modal lah yang memerlukan lahan untuk menginvestasikan uangnya yang telah menumpuk, karena bila dana tersebut tidak segera menemukan lahan untuk diinvestasikan maka uang tersbut akan mengancam kepentingan dan kesejahteraan pemilik uang tersebut. Tetapi dalam prakteknya ternyata para pemerintahan nasional khususnya pada dunia ketiga yang merengek-rengek agar modal mau masuk kenegaranya, dan bersedia melakukan segala syarat yang diberikan oleh kaum modal asalkan modal mau masuk kenegaranya.
Dengan alasan semakin meningkatnya persaingan modal maka para pemilik modal mensyaratkan agar negara dunia ketiga bersedia menjalankan sistem perburuhan yang fleksibel (Labour Market Flexibility) sebagaian bagian dari fleksibilitas produksi, selain persoalan tersebut maka yang menjadi syarat mutlaknya adalah diberikannya intensif pajak/pengurangan pajak dan pembebasan berinvestasi dimanapun dan pembebasan pasar hasil produksi yaitu dengan cara pengurangan pajak barang import.
Dalam hal pelaksanaan pasar kerja yang fleksible tersebut maka modal mempunyai keleluasaan dalam berinvestasi dan punya fleksibilitas dalam berproduksinya. Fleksibilitas dalam berproduksi dimaknain dengan diperbolehkannya outsourching pekerjaan maupun tenaga kerja serta meminimalkan jumlah pekerja tetap didalam perusahaaanya, karena pekerja tetap menimbulkan akibat meningkatnya kewajiban perusahaan dalam hubungan industrial dengan buruh yaitu adanya kewajiban membayarkan biaya pesangon bila mem-PHK buruh, biaya pensiun, bonus dll. Tetapi biaya-biaya tersebut dapat dipangkas habis bila hubungan industrialnya adalah berdasarkan sistem kerja kontrak ataupun sistem kerja outsourching. Dengan sistem outsourching maupun sistem kerja kontrak maka pemodal dapat terhindar dari pekerja yang kritis, karena bila ada pekerja yang mulai kritis terhadap sistem kerja yang ada maka pengusaha dapat dengan gampang meminta mereka digantikan oleh orang lain bila menggunakan sistem kerja outsourching tenaga kerja (lewat jasa tenaga kerja) atau tidak memperpanjang kontrak bagi buruh kritis yang dikontrak. Lewat fleksibilitas tenaga kerja ini juga pengusaha mampu mengatasi serikat buruh -yang selama ini menjadi penghalang bagi mereka dalam mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Serikat buruh menjadi mandul atau terancam bubar akibat anggotanya tidak lagi ada yang menjadi pekerja tetap diperusahaan tersebut, tidak adanya serikat buruh dipabrik adalah surga bagi pengusaha. Penyingkiran serikat buruh ini merupapakan implementasi dari paham individu dari sistem neoliberalisme ini. Buruh akan berhadapan secara individu dengan perusahaan tanpa ada lagi campur tangan negara dan serikat buruhnya.
Fleksibilitas tenaga kerja ini juga mengakibatkan semakin tajamnya persaingan antar buruh dalam mencari kesempatan bekerja diperusahaan hal ini mengakibatkan semakin kuatnya posisi pengusaha untuk membayar upah murah bagi buruh yang akan bekerja. Hancur nya ekonomi desa saat ini yang mengakibatkan besarnya angka migrasi pemuda desa kekota, hal ini membuat para pencari kerja (baik baru tamat smu/kuliah maupun buruh yang sebelumnya pernah bekerja) sering sekali tidak punya pilihan lain lagi dikota untuk menerima upah yang murah asalkan diterima bekerja. Sistem perburuhan dibawah neoliberalisme mensyaratkan negara harus terus mempertahankan adanya angka pengangguran yang besar agar posisi tawar buruh dan pencari kerja menjadi lemah bila berhadapan dengan pengusaha.
Kesewenang-wenangan pengusaha dalam menentukan upah selama ini masih sedikit terbatasi dengan masih ada nya kebijakan UMR hingga UMP/UMK/UMSP yang artinya adalah masih adanya campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja, dan tahapan lanjutan dari fleksibiltas tenaga kerja kaum neoliberal ini adalah memerintahkan negara untuk menghentikan sistem penentuan upah melalui mekanisme UMP/UMK/UMSP menjadi penentuan nilai upah ada ditingkat pabrik yaitu antara buruh dan pengusaha. Bila buruh yang bekerja tidak akan bisa menjadi sejahtera lalu apagunanya invesatasi tersebut masuk?
Untuk melaksanakan konsep ekonomi neoliberal ini maka peran pemerintahan nasional lah yang menjadi alatnya, lewat pembuatan undang-undang dan peraturan yang mendukung konsep neoliberal ini.
Pandangan ABM:
Benarkah upah buruh yang tinggi akan menyebabkan investasi tidak masuk ke Indonesia? Jelas, sekali lagi ini adalah propaganda “tukang obat” yang berusaha membohongi kita. Berikut bukti yang menunjukkan bahwa propaganda ini adalah bohong semata:
• Laporan lembaga PBB, UNCTAD tahun 1997 menyebutkan bahwa kemunculan perdagangan investasi spekulatif telah melemahkan komitmen investasi jangka panjang pada sektor-sektor produktif (investasi sektor riil). Tahun 2003 saja, uang yang ditanamkan pada investasi spekulatif ini dalam SEHARI saja mencapai 1,2 triltun dolar AS. Bandingkan misalnya dengan jumlah investasi yang ditanamkan pada sektor riil (produktif) di seluruh dunia yang pada tahun 2003 tidak mencapai 1 triltyun dolar AS dalam SETAHUN. Inilah kemudian sering juga disebut ekonomi kapitalisme neoliberal sering disebut ekonomi judi. Jadi investasi tidak masuk disebabkan karena para investor lebih tertarik “berjudi” dalam perdagangan spekulatif dalam bentuk perdagangan saham dan mata uang dibandingkan menanamkan modalnya bagi investasi riil seperti permbangunan suatu industri, bagun pabrik atau investasi riil lainnya. Jadi pemerintahan Indonesia selama ini hanya memfasilitasi spekulan/penjudi.
• Keengganan penguasa modal di dunia pertama untuk mengglobalkan investasinya. Hingga saat ini investasi masihlah berpusat di negara-negara dunia pertama. Laporan lembaga PBB, UNCTAD, World Investment Report 2003, menunjukkan bahwa lebih 71% investasi berada di negara-negara maju, 91% modal yang berasal dari negeri-negeri maju ditanamkan diantara sesama negeri-negeri maju. Artinya hanya kurang dari 9% modal dari negeri-negeri maju yang bergerak ke negara-negara diluar mereka.
• Upah buruh Indonesia tergolong rendah dan tidak ada korelasi/hubungan nyata antara upah rendah dengan masuknya investasi ke suatu negara. Hongkong dan Brunei yang menduduki peringkat 10 besar dalam urutan negara tujuan investasi dunia, justru upah buruhnya tergolong tinggi. Sementara upah buruh Indonesia masihlah tergolong rendah tetapi investasi tetaplah tidak masuk. Menurut Heri Rumwatin, Ketua Apindo Kabupaten Tangerang, dalam salah satu wawancara di bulan Agustus 2005, mengakui bahwa upah buruh masihlah rendah hanya 6-7% dari biaya produksi, justru yang memberatkan dunia usia adalah “biaya-biaya siluman” yang jumlahnya mencapai 10% dari biaya produksi. Perusahaan Sony yang memindahkan produksinya dari Indonesia ke Vietnam, juga menyatakan bahwa kepindahannya bukan disebabkan upah buruh melainkan karena biaya ekonomi yang tinggi diluar upah buruh (dikutip dari pernyataan ekonom UGM, Prof. Dr. Mas’ud Machfoedz dalam satu diskusi di Medan, 5 September 2006). Komponen Upah buruh Indonesia hanya 6-7% dari biaya produksi sedangkan bila kita bandingkan kenegara yang saat ini dsebutkan sebagai “saingan’ Indonesia dalam menggaet investor yaitu Malaysia(17%), China(30%) dan Vietnam(20%) maka cukup jelas bagi kita bahwa larinya dan tidak masuknya investasi ke Indonesia bukan karena kita kaum buruh, tetapi karena kegagalan dari pemerintah.
• Upah buruh Indonesia bukanlah persoalan utama yang dikeluhkan oleh pengusaha/investor. Persoalan yang paling dikeluhkan terutama pada adanya biaya: ketidakstabilan makro ekonomi; ketidakpastian kebijakan; korupsi pemerintah lokal dan pusat; pajak; biaya tinggi; tidak adanya kepastian hukum.
Dengan kondisi yang murah hingga saat ini dan fakta bahwa tidak ada hubungan antara tidak masuknya investasi dengan tingkat upah maka menjadi keputusan kita saat ini untuk memperjuangkan yaitu upah yang menjadikan kita kaum buruh sebagai manusia yang sesungguhnya bukan skedar sebagi alat kerja/mesin bagi pengusaha.
Penentuan upah selama ini dicoba secara sistematis untuk dapat memecah-belah kaum buruh, mulai membeda-bedakan buruh kerah putih dengan buruh kerah biru, penentuan upah pada tingkat propinsi dan kota serta pembedaan upah berdasarkan sektor kerjanya. Usaha tersebut selama ini hampir saja membuat perjuangan kita kaum buruh terjebak pada permainan yang diinginkan oleh kaum modal dan antek mereka dipemerintahan. Dengan membiarkan penentuan upah pada tingkat kota/kabupaten dan propinsi sebenarnya kita membiarkan pemerintahan nasional lepas tangan dari tugas pokoknya dalam perlindungan rakyatnya. Kita kaum buruh dipaksa terpecah perjuangan nya semata-mata memperjuangkan upah dikota/kabupaten kita saja, seakan-akan persoalan upah murah dikota/kabupaten lain bukanlah menjadi persoalan bagi kita. Sejarah telah mengajarkan kita termasuk sejarah perjuangan kita dalam menolak revisi UU 13/2003 kemaren bahwa hanya persatuan kaum buruh secara nasional lah kita mampu mempertahankan hak kita dan menuntuk hak lainnya. Penentuan upah berdasarkan sektor/UMSP jelas-jelas adalah usaha nyata untuk mengkotak-kotakkan kaum buruh kedalam sektornya, bahwa kita sadar betul bahwa persoalan kebutuhan hidup kaum buruh semuanya adalah sama tidak terbeda-bedakan semata-mata hanya karena perbedaan sektor kerja nya. Maka untuk mencapai Upah Layak tersebut secara bersama-sama maka ABM memutuskan untuk menuntut pemerintah dalam penentuan upah harus dilakukan secara nasional bukan berdasarkan kota/kabupaten apalagi sektoral. UPAH LAYAK NASIONAL yang menjadi tuntutan perjuangan kita saat ini.
Melihat hal tersebut maka ABM berkesimpulan bahwa pembangunan industri dengan mengandalkan dana dari investor asing selama ini bukanlah demi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia tetapi investasi tersebut hanyalah semata-mata difasilitasi oleh pemerintahan nasional selama ini demi kepentingan kaum modal internasional dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia serta mendapatkan tenaga kerja Indonesia yang murah. Yang tersisa dari proses investasi modal selama ini adalah kerusakan alam, buruh yang tetap miskin karena tereksploitasi oleh kaum modal selama ini, dan tidak ada kesejahteraan yang didapat. TUNTUTAN UPAH LAYAK NASIONAL tidak akan diwujudkan oleh pemerintahan yang pengabdiannya kepada kaum modal internasional.
Ketergantungan kepada investor asing dapat diibaratkan seperti ketergantungan kepada narkoba, kenikmatan sesaat yang didapatkan tidak sepadan dengan konsekuensi yang kita dapatkan berikutnya. Pengurangan angka pengguran saat investasi masuk sebenarnya dengan kondisi saat ini tidak akan membuat situasi secara nasional maupun bagi kaum buruh menjadi lebih baik karena kesejahteraan yang menjadi impian setiap orang yang bekerja tidak akan didapatkan dalam proses bekerja seperti saat ini.
Lalu kalau tidak dengan cara mendatangkan investor apakah kita sanggup menjalankan pembangunan? Pertanyaan seperti ini telah di jawab dengan tegas dalam konfrensi ABM tanggal 24-27 Juli 2006 di TMII jakarta, KITA MAMPU! Jalan keluar pembangunan nasional yang lepas dari ketergantungan pada investor asing dirumuskan dalam langkah:
- Penghapusan hutang Luar Negeri
- Nasionalisasi terhadap sumber daya alam (Pertambangan, Air, Listrik, Telekomunikasi) dan aset-aset vital lainnya
- Membangun industri nasional yang kuat
- Pemberantasan korupsi.
Dengan keempat langkah tersebut dan ditambahkan dengan proteksi terhadap pasar dalam negeri agar industri nasional yang sedang kita bangun tidak dihancurkan kembali oleh kerakusan kaum modal, serta industri nasional yang kuat dan maju tersebut harus berorientasi pada pasar dalam negeri. Program kerakyatan ini semata-mata hanya akan dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan yang pro rakyat dan berani melawan kaum modal internasional.
Sikap ABM Tentang Upah
Perjuangan untuk mendapatkan upah yang layak telah menjadi perjuangan kelas buruh sejak para kelas pekerja pertama kali muncul di atas muka bumi. Kurang lebih 8000 tahun lalu, para pekerja yang menggarap pembangunan piramida-piramida di Mesir telah mengadakan pemogokan untuk menuntut jatah makan yang lebih layak. Mereka memang bukan kelas buruh industrial seperti yang kita temui di jaman ini. Pada masa-masa tanam, mereka bekerja sebagai petani. Namun, di masa paceklik atau di masa antar-waktu tanam, mereka dipekerjakan oleh Kerajaan Mesir untuk membangun berbagai monumen, antara lain piramida dan makam para raja. Namun, di saat bekerja sebagai buruh pembangun monumen, mereka menerima upah layaknya sistem kerja buruh modern.
Sedemikian panjangnya sejarah perjuangan mendapatkan upah layak, kita jadi seringkali menganggap bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang memang semestinya dilakukan di bawah sistem masyarakat yang tidak berpihak pada rakyat pekerja. Tapi, apa sebenarnya “upah” itu? Mengapa para pemberi kerja memberi upah pada para pekerja? Seberapa besar semestinya upah sehingga dapat dianggap layak?
Mitos tentang Upah
Mitos 1: Upah adalah Harga Keringat Buruh
Pengertian yang banyak diterima umum mengenai upah adalah bahwa “upah” merupakan imbalan dari kerja yang diberikan buruh pada pengusaha. Dengan kata lain, pengusaha “membeli” kerja buruh. Namun argumen yang masuk akal ini dan bersahaja ini sesungguhnya mengandung banyak kesalahan dan akibat-akibat yang merugikan kaum pekerja.
Pertama, kerja bukanlah komoditi (barang dagangan) seperti yang biasa kita kenal. Bila kita menganggap bahwa buruh “menjual” kerjanya. Namun, demikian kerja itu diberikan pada pengusaha di tengah jam-jam panjang proses produksi yang melelahkan, kerja itu diserap dan diubah oleh proses produksi itu menjadi sebuah tambahan nilai pada produk yang dihasilkan. Dengan begitu, kaum buruh menjual sesuatu yang memberi tambahan kekayaan pada majikan kita. Jika benar pengusaha membeli “kerja” kita, tentunya ia akan membayar sebesar nilai yang kita hasilkan dalam proses produksi. Jika kita mau ambil kesejajaran dengan agak menyederhanakan persoalan, kita bisa membandingkan proses pembentukan harga ini dengan harga benda-benda aji yang konon dapat memberi kekayaan pada pemiliknya. Sebuah keris yang disebut bertuah dapat dihargai jutaan, bahkan puluhan dan ratusan juta rupiah. Itu karena si pembeli berkeyakinan bahwa besi aji itu dapat memberinya kekayaan. Namun, buruh (yang sudah pasti akan memberi kekayaan pada pengusaha) tidaklah dibayar puluhan juta rupiah – melainkan pada tingkat upah minimum. Kesimpulannya, sama sekali tidak benar bahwa pengusaha membeli “kerja” buruhnya.
Mitos 2: Upah sesuai Ketrampilan
Sekalian bicara tentang Upah Minimum. Inilah faktor kesalahan kedua dari argumen yang biasa kita pahami tentang upah. Jika benar pengusaha membeli “kerja” kita, maka ia akan memberi upah sesuai dengan ketrampilan yang kita miliki. Tapi, bukan itu yang kita temui dalam praktek. Kenyataannya, pengusaha selalu berusaha menghitung upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup¬-nya. Mau itu disebut Kebutuhan Fisik Minimum, Kebutuhan Hidup Minimum, atau Kebutuhan Hidup Layak – tetap kebutuhan yang menjadi dasar perhitungan, bukan keterampilan. Di samping itu, tingkat kebutuhan yang diakui oleh pengusaha, telah terbukti, tergantung pada negosiasi antara kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha. Jika kita bicara tentang negosiasi atau perundingan, kita bicara tentang perimbangan kekuatan antar pihak-pihak yang berunding. Kita juga sudah lihat bagaimana perjuangan untuk upah biasa melibatkan demonstrasi dan mogok kerja yang ditujukan untuk menekan lembaga-lembaga publik (negara) yang berwenang menetapkan upah. Dengan demikian, bukan nilai “kerja” yang menjadi landasan bagi penentuan upah, melainkan tingkat kebutuhan buruh, yang pengakuannya ditentukan lebih lanjut oleh tekanan dan perjuangan politik.
Mitos 3: Upah harus disesuaikan dengan Hukum Pasar
Adanya negosiasi upah dan diakuinya anggapan umum bahwa kerja adalah sebuah “komoditi” menimbulkan kesalahan yang ketiga, yakni anggapan bahwa dalam penentuan nilai kerja (=upah) berlaku hukum pasar, yakni permintaan dan penawaran. Padahal, dalam pengalaman praktek sehari-hari serikat buruh, bukan hukum pasar ini yang berlaku dalam perundingan. Melainkan di mana serikat buruhnya kuat, upah dan jaminan sosial lainnya pasti diberikan secara penuh – tidak jarang bahkan masih dilebihkan. Namun, di mana serikat lemah, hampir bisa dipastikan bahwa kesejahteraan juga tidak terjamin. Selain dari persoalan kekuatan serikat, yang artinya seberapa kuat posisi tawar buruh, upah yang tinggi biasanya ditemui di perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan keuntungan luar biasa besar.
Keuntungan bagi Pengusaha
Dengan argumen palsu itu, pengusaha dapat menerapkan berbagai sistem yang menguntungkan mereka. Yang pertama berkaitan dengan masalah “produktivitas”. Dengan alasan bahwa mereka sedang “membeli kerja”, pengusaha berusaha menekan buruh agar berproduktivitas setinggi mungkin. Entah dengan tekanan dan ancaman, atau dengan pemberian insentif, pengusaha berusaha memeras keuntungan semakin banyak dari keringat buruhnya. Padahal, kita sudah lihat bahwa mereka hanya memberi upah sebatas “kebutuhan hidup”. Sekalipun ada insentif, jumlahnya pastilah sangat jauh di bawah nilai tambah yang kita berikan pada pengusaha lewat kerja kita. Di samping itu, dengan bekerja melebihi batas kemampuan fisik dan mentalnya, seorang buruh justru memperpendek usia produktivitasnya sendiri. Kelelahan memicu penyakit dan penuaan dini. Selain daripada itu, semakin panjangnya waktu yang dihabiskan di tempat kerja (misalnya karena lembur), akan membuat keluarga tidak terurus – satu sumber stress dan tekanan lain bagi kesejahteraan buruh.
Untuk memberi kesan bahwa pengusaha sungguh-sungguh membeli keterampilan, kini diterapkan komponen upah tambahan berdasarkan sektor. Sektor-sektor yang dianggap membutuhkan ketrampilan tinggi akan mendapatkan upah minimum sektoral yang lebih tinggi dari sektor-sektor industri berteknologi rendah. Peraturan ini tengah diterapkan, misalnya saja, pada sektor otomotif. Namun, ukurannya kemudian menjadi rancu karena penentuan sektoral itu ditentukan oleh seberapa tinggi teknologi yang diterapkan oleh industri – bukan oleh seberapa terampil buruhnya. Satu pertanyaan sederhana: apakah seorang buruh bangunan yang menggunakan peralatan sekedarnya memang kurang terampil dibandingkan seorang operator robot pembuat mobil? Seorang buruh bangunan harus mengerahkan segenap ketrampilannya untuk membuat bangunannya kokoh dan dapat bertahan lama, sementara seorang operator robot cukup menekan beberapa tombol untuk menggerakkan robotnya. Siapapun yang pernah mencoba memasang sendiri ubin keramik (tanpa memanggil tukang) pasti tahu betapa sulitnya pekerjaan itu, dan betapa pekerjaan yang kelihataannya sederhana itu ternyata membutuhkan ketrampilan yang amat tinggi. Terlebih jika tidak memiliki peralatan yang memadai. Semakin tinggi teknologi, justru tingkat ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya semakin rendah.
Dan melalui anggapan bahwa dalam penentuan upah berlaku hukum pasar, kelas pengusaha kemudian melancarkan tuduhan bahwa serikat buruh merupakan sebuah kekuatan yang “mendistorsi pasar” – dengan kata lain, serikat buruh adalah sebuah kekuatan monopoli, yang harus dihapuskan, sehingga sistem persaingan pasar dapat berjalan dengan lancar. Kenyataan yang kita temui, setelah serikat dibubarkan (biasanya pasca relokasi atau PHK massal), pengusaha melakukan tawar-menawar dengan intimidasi: “kalau kamu tidak mau menerima tingkat upah yang kami tawarkan, masih banyak orang lain yang kini menganggur ingin juga bekerja di sini.” Dengan kata lain, “hukum pasar” pada prakteknya adalah alat intimidasi agar buruh mau menerima tingkat upah yang murah. Hukum Pasar bukanlah sebuah hukum alam, atau hukum yang berlaku secara objektif, melainkan sebuah akal-akalan karangan pengusaha agar dapat menekan tingkat upah buruh.
Hakikat Upah
Dua segi dari Kerja
kerja manusia mengandung dua aspek yang sebenarnya tidak terpisahkan: (1) kemampuan manusia menghadirkan kerja itu, dan (2) kerja riil yang dilakukannya atas material produksi tertentu. Sederhananya, kedua aspek itu adalah (1) kesehatan fisik dan mental si buruh agar dapat hadir di pabrik; dan (2) hasil produksinya. Dari kedua aspek kerja manusia ini, ternyata pengusaha hanya membayar untuk aspek pertama, kemampuan manusia untuk menghadirkan kerja. Pengusaha tidaklah membayar seorang buruh untuk kerja yang dilakukannya di pabrik, melainkan untuk menjaganya agar tetap dapat hadir di pabrik. Karena seorang buruh akan terus hadir selama ia sehat, maka ia akan diupah sesuai jumlah biaya yang dibutuhkannya agar tetap sehat. Itulah mengapa pengusaha hanya mau mengupah berdasarkan kebutuhan.
Kadang kala, misalnya di pabrik-pabrik mapan yang skala produksi dan modalnya cukup besar, prestasi kerja juga dibayar – contohnya dalam bentuk insentif atau remunerasi atau skala prestasi.
Sistem kerja upahan adalah satu tiang pokok ketidakadilan dalam sistem kapitalis. Berapapun besar upah yang kita terima, tetap saja tidak ada apa-apanya dibandingkan besarnya nilai-lebih yang kita serahkan pada pengusaha dalam produksi. Buruh hanya dibayar cukup untuk dia hidup, tetap datang ke pabrik esok hari, dan tetap produktif.
Perjuangan Untuk Upah
Apakah Pengusaha berniat baik ketika menaikkan upah?
Sejalan dengan perkembangan proses produksinya, pengusaha menyadari bahwa jika buruh hanya diupah cukup untuk sekedar makan-minum, barang-barang produksi kapitalis tidak akan dapat diserap pasar. Ini karena dalam masyarakat industrial, mayoritas anggota masyarakat adalah buruh. Dengan demikian, buruh adalah juga konsumen yang diandalkan kapitalis untuk membeli produknya. Melalui iklan dan promosi, pengusaha membuat buruh “membutuhkan” produk tertentu. Contohnya: kalau dulu buruh tidak butuh deodoran, sekarang itu sudah jadi kebutuhan primer buruh. Pengusaha pada dasarnya hanya mau mengupah sebesar “biaya produksi” untuk menghasilkan kemampuan buruh bekerja – dengan kata lain: biaya kebutuhan hidupnya. Namun, agar buruh mampu menjadi konsumen bagi produk yang dihasilkan pengusaha, komponen yang harus diperhatikan untuk menghitung upahnya pun semakin bertambah.
Kebutuhan objektif kapitalisme untuk membuat buruh menjadi konsumen, dan perjuangan naluriah buruh untuk lepas dari kesengsaraan dan kemiskinan, telah membuka ruang bagi perjuangan upah. Pengusaha dan buruh bertarung untuk menentukan apa saja komponen atau item yang termasuk dalam “kebutuhan hidup” buruh. Buruh tentu saja ingin agar semua kebutuhan hidupnya terpenuhi, sementara pengusaha ingin tetap mempertahankan tingkat upah serendah mungkin.
Kesimpulannya, pengusaha hanya menaikkan upah supaya buruh bisa semakin konsumtif. Kenaikan itupun tergantung kekuatan buruh untuk memaksa pengusaha mengakui bahwa kebutuhan hidup buruh telah bertambah.
Hakikat Perjuangan untuk Upah
Dengan demikian, jika kita perhatikan hakikatnya, perjuangan untuk peningkatan upah bukanlah perjuangan sejati untuk menghapuskan ketidakadilan dalam sistem kapitalis. Perjuangan itu adalah untuk merebut kembali sebagian dari kekayaan yang telah diperas dan dihisap kapitalis dari kerja buruh.
Upah dan Negara
Negara biasanya didirikan dengan tujuan menyejahterakan rakyat. Setidaknya itulah yang biasa disebutkan dalam pembukaan UUD satu negara – contohnya saja Pembukaan UUD 1945. Namun, pada kenyataannya, Negara (dalam hal ini pemerintah) Indonesia lebih banyak berpihak pada pengusaha daripada kepada buruh. Sejak Pemerintahan Orde Baru berdiri, buruh telah dianggap dan diperlakukan sebagai sapi perah bagi kepentingan segelintir pengusaha. Di masa Orde Baru kita ingat bahwa “upah murah” dijadikan primadona untuk menarik pengusaha asing. Masih di masa Orde Baru, buruh kita dikirim ke luar negeri, dijadikan TKI, yang nasibnya terlunta-lunta di negeri orang. Saat ini, kita mendengar slogan “ramah investasi” yang ternyata artinya adalah menerapkan sistem kontrak dan outsourcing. Ujung-ujungnya adalah membebaskan pengusaha dari keharusan membayar upah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menghitung Upah yang Layak
Jika kita menerima bahwa perjuangan upah merupakan perjuangan yang berada dalam kerangka kapitalisme, maka dasar penetapan upah tetaplah proses jual-beli antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian, tingkatan upah haruslah sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk menghadirkan kemampuan kerja seorang buruh yang sehat secara fisik dan mental di pabrik.
Kebutuhan Fisik, dapat dijabarkan sebagai kebutuhan untuk menjaga kesehatan ragawi buruh, agar ia dapat bekerja dengan segenap tenaga dan sanggup berkonsentrasi penuh selama bekerja. Dengan demikian, komponen pokok dari Kebutuhan Fisik adalah kecukupan gizi, baik untuk tubuh maupun otak. Tapi, untuk dapat menghadirkan seorang yang sehat ke dalam proses kerja, dibutuhkan pula biaya untuk menciptakan kesempatan beristirahat dan memulihkan (restorasi) tenaga yang telah dihabiskan dalam proses produksi. Komponen biaya tempat tinggal (termasuk listrik dan air) dan rekreasi masuk dalam kategori ini. Di samping itu, seorang buruh harus juga menjaga kesehatan fisik dan lingkungannya – antara lain dengan mandi, berpakaian yang layak dan sehat, dan berolahraga. Komponen pokok terakhir adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan buruh tersebut secara fisik di pabrik – dengan kata lain, biaya transportasi.
Kebutuhan Mental, mencakup persoalan bagaimana buruh tersebut menjaga martabat dirinya di tengah pergaulan sosial. Oleh karena itu, kebutuhan berhias diri dan keterlibatan dalam aktivitas sosial di tengah lingkungan tempat tinggal harus pula ditanggung oleh pengusaha yang membeli tenaga buruh tersebut. Seorang buruh juga harus terus meng-upgrade dirinya, meningkatkan pengetahuannya agar tidak menjadi bahan olok-olok sosial semacam gaptek atau gagap teknologi. Ia harus banyak membaca dan mendengar/menonton berita, ia juga harus mendapatkan buku-buku yang dapat menuntunnya lebih memahami dunia. Selain itu, seorang buruh, sebagai manusia, juga memiliki kebutuhan komunikasi. Maka, biaya komunikasi jarak jauh juga harus masuk dalam komponen upah.
Kebutuhan lain yang mencakup sekaligus Kebutuhan Fisik dan Mental adalah Kebutuhan Berkeluarga. Tiap orang butuh untuk mendapatkan pasangan hidup, dan meneruskan keturunannya. Kebutuhan ini seringkali bersesuaian dengan tuntutan sosial dan spiritual yang diberlakukan masyarakat. Oleh karena itu, perhitungan atas upah tidak boleh berdasarkan kebutuhan orang lajang semata, melainkan harus memperhitungkan kebutuhan untuk berkeluarga. Dengan kata lain, seorang buruh harus dianggap berkeluarga dan memiliki anak ketika menentukan upahnya.
Komponen-komponen ini telah menjadi kebutuhan hidup yang penting secara sosial bagi buruh Indonesia pada saat sekarang. Oleh karena itulah, perjuangan upah pada saat ini berarti pula perjuangan untuk membuat pengusaha dan pemerintah mengakui bahwa inilah yang dibutuhkan buruh dalam kehidupannya.
Kesimpulan tentang Upah
Menimbang berbagai faktor di atas, maka sudah sepantasnya program yang diperjuangkan Aliansi Buruh Menggugat adalah Upah Layak Nasional. Perjuangan Upah Layak Nasional adalah sumbangsih yang sangat besar dari gerakan buruh terhadap kemajuan peradaban di negara Indonesia.






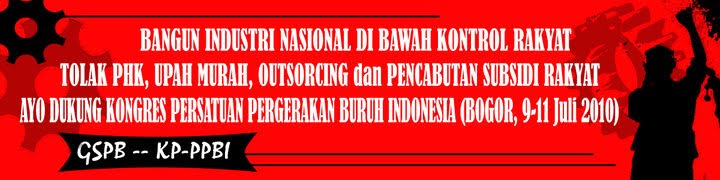
|